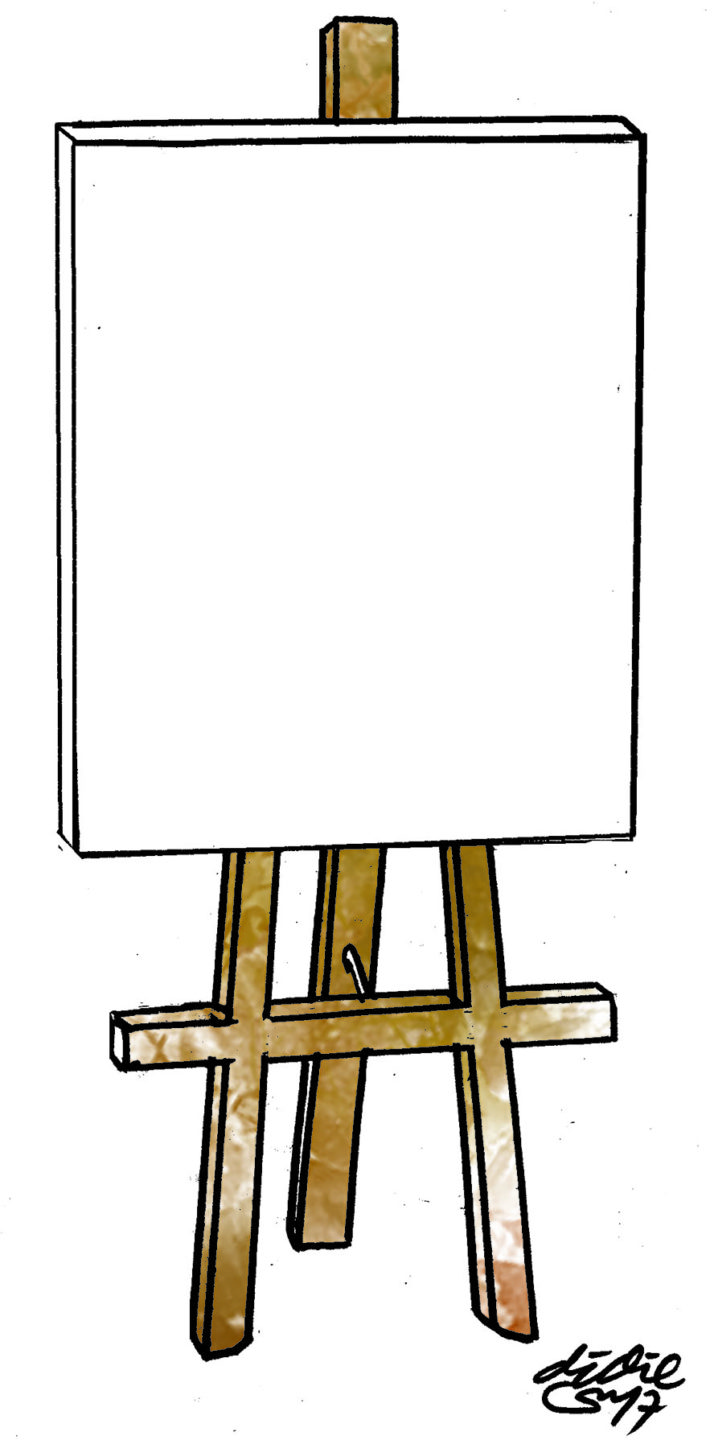
.
Mesti diakui, istilah kebudayaan—terlepas dari apa yang dipahami tentangnya—belakangan jadi bahan perbincangan atau sorotan media publik.
Negara, melalui pemerintah, seolah menaruh perhatian besar pada masalah di seputar istilah tersebut. Setidaknya lewat berbagai wacana hingga simbol-simbolnya, seperti yang ditampilkan dalam perayaan kemerdekaan di Istana Negara beberapa waktu lalu. Bahkan, Persatuan Purnawirawan AD pun baru-baru ini menyelenggarakan seminar nasional mengenai hal tersebut, entah berdasar urgensi apa.
Namun, di tengah pergumulan diskursif yang sebenarnya lebih dipenuhi ungkapan sloganistik itu, ternyata masih sering kita temukan pengertian yang salah kaprah memahami kebudayaan (di tingkat ideal/abstrak hingga konkret/praksisnya). Hal ini terjadi tidak hanya pada masyarakat umum secara wajar, tetapi juga di kalangan terdidik atau kelas menengah. Lebih mengkhawatirkan lagi, kekeliruan itu pun terjadi hampir secara permanen di kalangan elite, khususnya mereka yang punya kuasa menentukan kebijakan.
Dalam pemahaman keliru itu, kebudayaan bukan saja dimunculkan dan dibesar-besarkan menjadi semacam bubble atau gelembung besar yang kosong, secara politis dan sosial, tetapi juga disikapi dan dikonkretkan dalam kebijakan yang jika tidak dipinggirkan, dinafikan, bahkan cenderung dihina oleh mereka: para pengambil kebijakan, di pusat ataupun di daerah.
Di tingkat infrastruktur, atau lebih dini lagi dalam anggaran negara (APBN), apa yang dulu saya sesalkan di depan presiden terdahulu—negara menghina kebudayaan dengan memberi anggaran hanya Rp 2.000 per kapita untuk mengurus begitu banyak hal di seputar bidang itu—ternyata tidak berubah sama sekali keadaannya hingga hari ini. Presiden keenam yang saya kritik itu akhirnya menaikkan anggaran kebudayaan lebih dari dua kali lipat pada APBN 2015 menjadi Rp 1,7 triliun, katakanlah menjadi Rp 6.000 atau sekitar 2,5 dollar AS per kapita.
Masih sangat belum memadai, tetapi mungkin memberi sinyal baik, seperti ditunjukkan APBN berikutnya yang disusun pemerintahan baru, menambah anggaran kebudayaan (walau sedikit) menjadi Rp 1,85 triliun. Namun, dalam APBN-P tahun yang sama, jumlah itu malah menyusut jadi Rp 1,5 triliun.
Di banyak daerah pun kondisinya serupa. Taman Budaya Medan, Sumatera Utara, misalnya, sudah lama disebut "rawa" atau kolam buaya karena setiap hujan deras auditorium utama menciptakan kolam air yang tidak hanya menghalangi ekspresi seni, tetapi juga sukses merangsang imajinasi seniman setempat membayangkan reptil purba santai bermukim di kolam itu. Atau salah satu provinsi di Jawa, mengalokasikan dana untuk dewan kesenian setempat hanya Rp 75 juta per tahun. Nilai yang bahkan terlalu minim untuk membuat satu perhelatan seni/pertunjukan saja. "Apa ini bukan penistaan atau penghinaan pada kebudayaan?"
Di Ibu Kota, kondisinya setali-segobang. Anggaran kebudayaan dalam APBD 2018 di kisaran Rp 100 miliar dari total APBD yang Rp 77 triliun lebih. Itu pun, tentu saja, harus dibagi dua dengan urusan pariwisata. Sebuah kode politik yang memberi makna bahwa kebudayaan sama sekali tidak lebih penting, bahkan dari urusan pemuda dan olahraga yang tiga kali lipat budgetnya, bidang komunikasi dua kali lipat. Anggaran kebudayaan malah lebih rendah daripada urusan (dinas) pemadam kebakaran.
Jika ditanya langsung, semua pejabat negara/publik tentu dengan penuh bunga kata-kata akan melambungkan posisi dan fungsi kebudayaan yang fundamental dalam pembangunan. Semua jawaban yang menyiratkan betapa para pengambil kebijakan di negara ini memang mempermanensi komprehensi yang keliru, sebagai pre-teks untuk tidak membuang uang bagi kegiatan bergenit-genit di dunia artistika atau estetika.
Pembangunan tiada adab
"Bergenit-genit" tentu saja adalah ekspresi yang sinistik terhadap pemahaman para pengambil kebijakan terhadap kebudayaan sebagai "hanya" kerja di seputar kesenian. Praktik kebijakan pemerintah di semua levelnya hanyalah turunan atau konsekuensi logis dari pemahaman yang keliru-akut tentang kebudayaan. Apa yang diurus dan dihasilkan dari semua kebijakan itu hanyalah bentuk-bentuk yang dominan material/fisikal, yang tidak lain merupakan "produk kebudayaan", bukan kebudayaan itu sendiri selaku produsen dari semua produk berbentuk artefak, ecofak, ideofak, dan sebagainya.
Kebudayaan yang dijargonkan sebagai fondasi atau tulang-tulang dari gedung pembangunan tentu saja bukanlah manekin-manekin yang genit secara artifisial juga virtual itu. Dia tidak lain adalah produsen yang memungkinkan manusia atau sebuah bangsa memproduksi karya-karya yang menjadi indikator, tolak ukur, juga isi dari pembangunan itu. Dia adalah sebuah khazanah abstrak berisi ide-ide (yang idealistik, bisa dipelesetkan jadi "ideologis") dari sebuah komunitas atau bangsa yang berisi wawasan dunia (weltanschauung), di mana visi (masa depan) dan misi (cara mencapainya) menjadi "keluaran"-nya.
Maka, sungguh hidup (baca: pembangunan) akan sia-sia jika hanya disibukkan dengan menghias produk-produk kebudayaannya, bukan ide atau gagasan di baliknya, bukan apa yang dapat menghasilkan itu semua, bukan manusia di mana ide itu berkelindan di dalamnya. Kesia-siaan itu akan terbukti ketika semua pembangunan infrastruktur, misalnya, baik yang fisik, sistemik, maupun institusional tidak berfungsi, bahkan rusak total ketika manusia sebagai pengguna atau pengelolanya tidak memiliki adab (yang diisi oleh kebudayaan) di dalam dirinya. Manusia itu tidak hanya akan memanipulasi, mengkhianati, tetapi juga mendestruksi semua (pem)bangunan(an) itu demi kepentingan sektoral/sektarian atau individual, seperti terlihat pada melimpahnya kasus kriminal di kalangan pejabat publik dan swasta belakangan ini.
Keadaban bangsa kita pun merosot drastis sebagaimana terlihat mulai dari jalan raya hingga gedung tinggi yang dihuni para pejabat pengemban amanah konstituen atau rakyatnya. Ketakberadaban yang kita perlihatkan dengan pengingkaran juga pengkhianatan pada simbol-simbol, properti, hingga konstitusi negara itu sebenarnya menjadi bukti apabila kebudayaan tidak dapat dimengerti (melulu) sebagai urusan seputar "genat-genit" seni, tradisi, cagar budaya, atau galeri. Namun, juga dengan semua tindakan sosial kita, pada semua dimensi kehidupan kita.
Manusia subyek utama
Posisi, peran, dan fungsi kebudayaan, seperti terpapar di atas, selayaknya jadi bagian dari strategi kebudayaan, basis atau landasan dari proyek pembangunan yang kita kerjakan secara represif saat ini. Pembangunan yang secara imperatif memberi fokus yang cukup besar pada pembangunan manusia sebagai aktor atau pemeran utama dari saga pembangunan ini. Karena cuma manusia yang mampu melakukannya, dan karena memang manusia yang menciptakan, mengembangkan, dan mampu merusaknya. Karena, justru, pembangunan manusia adalah tujuan dasar dan utama kebudayaan.
Karena itu, apa yang secara normatif kita sebut sebagai "peningkatan SDM" bukanlah sekadar meningkatkan kapasitas fisikal atau intelektual saja, terlebih intelektualitas untuk sekadar jadi "tukang" (vokasional). Akan tetapi, SDM yang juga berkualitas dalam kapasitas mental-psikologikal dan spiritualnya. Manusia yang hidup dalam kesadaran sinergis dan integratif di antara empat kapasitas atau kesadaran ilahiahnya: fisikal, intelektual, mental, dan spiritual.
Saya memandang, apabila kita masih mengacu pada konstitusi, apalagi mukadimahnya, "kecerdasan bangsa", sebaiknya dielaborasi dari pemahaman kultural di atas. Elaborasi yang tentu saja tidak dalam program-program terurai di bagian atas, apalagi jika penyelenggara negara mengikuti turunan konseptual-regulatifnya dalam UU Pemajuan Kebudayaan. UU yang jika dilaksanakan bukan saja berpeluang menciptakan bias dan kekeliruan, juga menciptakan kerapuhan pada bangunan materialistik negara ini.
Sebagai acuan konstitutif pemerintah, UU di atas sudah membingungkan mulai dari judulnya. Apa yang hendak "dimajukan" dari kebudayaan? Apakah manusia yang jadi tujuan dari terciptanya budaya itu? Karena, ternyata kata manusia, terlihat tidak menjadi bagian utama dalam isi dan tujuan UU tersebut. Kata kerja terpenting, yang tampaknya jadi turunan kata "pemajuan" dalam judul, yakni pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Merujuk pada batasan atau rumusan (sangat) pendek tentang kebudayaan di pasal terawal, sebagai "hasil karya masyarakat", tentu saja kata kerja itu lebih tertuju pada "produk", bukan kebudayaan sebagai produsen atau manusia sebagai aktor utama.
Hal itu menjadi jelas dalam keseluruhan isi UU yang menempatkan "obyek kebudayaan" justru sebagai subyek utama dari "pemajuan", yang tak lain adalah produk atau "hasil karya". Inilah substansi yang berulang kali saya tegaskan kepada sejumlah pihak yang merasa paling otoritatif menyusun UU itu. Judul UU, karena itu, jika ia harus ada, sebaiknya menggunakan istilah "Produk Kebudayaan", di mana negara bukan saja bisa, tetapi wajib mengurus/mengembangkannya.
Kebudayaan jangan sampai dikerdilkan begitu tragisnya hingga hanya menjadi sekadar "obyek". Sebuah strategi pembangunan yang berkebudayaan harus memilih "subjek" utamanya manusia, sebagaimana menjadi imperasi konstitusi. Karena dengan subyek manusia, katakanlah dalam frase "karakter/pribadi yang berkebudayaan" ala Sukarno, pembangunan akan jauh lebih memberi makna pada manusia/masyakarat yang juga secara substansial menjadi subyek pembangunan.
Pemerintah, juga siapa dan apa pun di negeri ini, sebaiknya melepas obsesi dan ilusi mereka untuk menyetir atau mengendalikan kebudayaan. Sebaiknya, jika tidak mampu terlibat dalam diskursus tanpa akhir dari kebudayaan nasional kita yang bahari dan purba ini, mereka berkontribusi dalam menciptakan ruang-ruang yang lebih lapang bagi terjadinya diskursus yang kadang memang turbulensif itu.
Dengan kontribusi—yang dapat dilakukan dengan mengorbankan atau menghibahkan sebagian dari kapasitas berlebih yang dimilikinya, baik dalam bentuk fasilitas, finansial, jaringan, akses, relasi, dan sebagainya—itu, para pelaku kebudayaan dapat leluasa berkreasi, berekspresi, dan menyalurkan inovasinya atau gagasan-gagasan pembaruannya di pelbagai lapangan kehidupan. Melahirkan karya-karya kebudayaan yang pada akhirnya memberi makna dan fungsi positif bagi pemerintah dan kaum elite itu sendiri.
Bukankah negeri semacam itu yang kita idamkan, yang menjadi visi para pendahulu kita? Bukankah negara semacam itu yang memiliki daya saing tinggi, atau mampu menaikkan kedaulatan juga derajat bangsanya?
Radhar Panca Dahana

Tidak ada komentar:
Posting Komentar